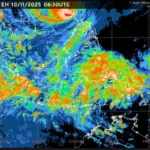SAAT melewati toko pecah-belah, Senin (25/8/2025) malam lalu, istri saya menunjukkan seikat rotan yang dijual toko.
Oleh: Sultan Yohana
“Untuk apa itu?” tanya saya benar-benar tak tahu.
“Untuk pukul pantat,” jawabnya.
“Really?” saya tak percaya dengan jawaban istri. Di negeri semodern Singapura, masih jual rotan untuk memukul anak-anak? WTF?
Istri menambahkan, ibunya dulu, punya sebiji rotan serupa yang dipakai memukul anak-anaknya kalau nakal, termasuk dirinya. Salah satu orangtua murid istri, kata dia, di rumahnya tersedia tiga bilah rotan pemukul. Whaladalah…
Sejauh ini, selama 14 tahun tinggal di Singapura, saya benar-benar tak tahu ada tradisi memukul anak-anak (sendiri) pakai rotan. Tradisi yang memunculkan potensi bisnis berjualan rotan pemukul.
Di kota saya, Malang, saya tak mengenal tradisi memukul anak-anak dengan rotan. Saya pribadi, di rumah, tak pernah sekalipun dipukul atau ditampar ibu. Paling kalau sudah saking jengkelnya atas kenakalan saya, ibu akan mencubit paha saya.
Selain orangtua, di jaman saya, hanya guru yang diberi hak memberi hukuman secara fisik. Bentuknya macam-macam, tak hanya memukul. Guru ngaji saya, Lek Mut, dulu biasa memukul kami dengan penggaris kayu. Guru Tajwid saya, Pak Saidun, kerap memukul jari tangan kami dengan penggaris kayu yang besar, atau menarik rambut godeg ke atas hingga memerah. Pak Manan, guru Quran-hadis, memilih mencubit paha kami hingga membiru. Tapi dari semua jenis hukuman itu, tak ada alat yang benar-benar dikhususkan untuk menggebuk. Sebagaimana rotan pemukul yang dijual di toko pecah-belah Singapura tadi.
Rotan pemukul, sebuah “kearifan lokal” yang kontradiktif, dan uniknya, masih bertahan hingga kini. Kontradiksi, mengingat bagaimana Singapura begitu getol memerangi kekerasan fisik pada anak-anak.
(*)
Penulis/ Vlogger : Sultan Yohana, Citizen Indonesia berdomisili di Singapura. Menulis di berbagai platform, mengelola